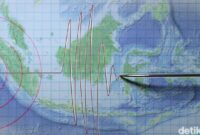Ada satu pertanyaan bodoh saya yang terlampau revolusioner, namun wajar bagi seorang mahasiswa yang baru mulai menggandrungi diskusi kajian politik, demokrasi dan pergerakan di kampus ketika itu. Pertanyaannya adalah: “Mengapa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat masih bertahan sampai hari ini?”
Padahal Yogyakarta adalah kota pelajar dan ada UGM yang notabenenya adalah kampus pergerakan. UGM berdiri kokoh di Yogyakarta bersama dengan suara-suara kritiknya yang lantang pada pemerintah pusat di Jakarta, namun tidak bisa meruntuhkan monarki di depan matanya.
Pertanyaan itu ternyata menghantui saya sejak awal perkuliahan hingga berakhirnya masa studi dan mendorong saya untuk berusaha memahami cara pandang masyarakat Yogyakarta terhadap Sultan, baik sebagai raja tradisional maupun sebagai gubernur modern.
Istilah enklave monarki saya kutip dari sebuah penelitian berjudul “Obedient liberals? Mass attitudes in a monarchy enclave” oleh seorang akademisi UGM bernama Arya Budi. Enklave artinya daerah (wilayah) budaya yang terdapat di dalam wilayah budaya lain. Yogyakarta dengan status keistimewaannya yang mengizinkan adanya monarki di wilayah tersebut merupakan enklave atau bagian dari NKRI yang menganut sistem demokrasi.
Arya Budi dalam penelitiannya menyebut masyarakat Yogyakarta sebagai “obedient liberals” alias kaum liberal yang patuh. Menjadi keunikan tersendiri bahwa masyarakat Yogyakarta bukanlah masyarakat yang terbelakang, melainkan masyarakat modern yang juga menganut nilai-nilai liberal seperti kebebasan berpendapat, kesetaraan gender dan berpartisipasi aktif dalam politik nasional, tetapi tetap patuh dalam konteks hidup di bawah pemerintahan monarki oleh Sultan Yogyakarta.
Tulisan ini saya harap dapat membantu masyarakat Indonesia di luar Yogyakarta untuk bisa memahami cara berpikir masyarakat Yogyakarta yang sangat bangga dengan status keistimewaan dan agar masyarakat umum tidak mensimplifikasi makna keistimewaan Yogyakarta. Fenomena yang terjadi di Yogyakarta dapat dimaknai sebagai khazanah atau variasi dalam berdemokrasi ala Indonesia.
Yogyakarta “Memilih” untuk Bergabung dengan Republik
Ketika saya membuat skripsi tentang analisis framing Krjogja.com sebagai salah satu media lokal yang berfungsi sebagai penyedia ruang publik bagi masyarakat lokal di Yogyakarta dalam memberitakan topik status keistimewaan Yogyakarta, terdapat satu argumen yang menonjol dalam diskursus mengenai alasan keistimewaan DIY bertahan sampai hari ini, yaitu Sejarah.
Sebelum kemerdekaan Yogyakarta merupakan sebuah wilayah otonom yang memiliki segara sarana dan prasarana penunjang untuk menjadi negara merdeka sendiri. Kendati demikian, Yogyakarta memilih untuk bergabung dengan Republik.
Yogyakarta memiliki sejarah panjang sebagai pusat budaya Jawa dan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sultan Hamengkubuwono IX, yang memerintah sejak 1940, memainkan peran kunci selama masa perjuangan kemerdekaan dan era pemerintahan Sukarno dan Suharto. Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota darurat Indonesia pada tahun 1948, di mana Sultan HB IX membantu membayar gaji kabinet dan staf pemerintah.
Pada tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam VIII menyatakan bahwa wilayah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui dekrit kerajaan yang dikenal sebagai “Amanat 5 September 1945”.
Sehari setelahnya, pada 6 September 1945, pemerintah pusat memberikan Piagam 19 Agustus 1945 sebagai bentuk penghargaan atas bergabungnya Yogyakarta dengan RI.
Bergabungnya Yogyakarta dalam NKRI menjadikan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dengan wilayah kedaulatan yang lebih luas. Setelah itu, Soekarno memberikan payung hukum khusus dan status istimewa terhadap Yogyakarta sebagai daerah dalam Indonesia.
Identitas kolektif masyarakat Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh monarki yang telah lama berkuasa. Masyarakat Yogyakarta menunjukkan sikap “liberal patuh,” di mana mereka mendukung nilai-nilai liberal seperti hak-hak perempuan dalam politik, tetapi juga bangga dengan sistem monarki yang ada. Sikap ini mencerminkan habituasi dan identitas kolektif yang kuat, di mana monarki membantu membedakan mereka dari masyarakat di provinsi lain atau negara lain.
Yogyakarta dikenal dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan paparan terhadap modernitas, tidak ada catatan protes yang menuntut pemilihan gubernur. Sebaliknya, masyarakat Yogyakarta pernah melakukan protes besar-besaran menentang upaya pemerintah pusat untuk mengadakan pemilihan gubernur melalui RUU Keistimewaan Yogyakarta pada tahun 2009-2010. Protes ini menunjukkan dukungan kuat masyarakat terhadap sistem monarki (status quo) yang ada.
Demokrasi Prosedural dan Demokrasi ala Masyarakat Yogyakarta
Sejak reformasi, status keistimewaan Yogyakarta telah menjadi polemik setidaknya dalam dua momentum. Pertama di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ketika hendak merumuskan RUU Keistimewaan Yogyakarta, lalu pada akhir tahun 2023 ketika politisi PSI Ade Armando mengeluarkan pernyataan bahwa DIY menjalankan praktik politik dinasti. Keduanya terjadi akibat adanya simplifikasi dalam memaknai status keistimewaan.
Kita memang dapat mendefinisikan bahwa DIY menjalankan sistem monarki dengan tidak adanya pemilihan gubernur sebagaimana di provinsi lain.
Demokrasi seringkali dipahami sebagai sistem politik yang mengutamakan pemilihan umum yang bebas dan adil. Namun, di Yogyakarta, kita menemukan bentuk demokrasi yang unik dan berbeda dari konsep demokrasi prosedural yang umum dikenal.
Penelitian yang dilakukan oleh PolGov Universitas Gadjah Mada menunjukkan adanya fenomena unik di Yogyakarta. Masyarakat disana mendukung nilai-nilai liberal seperti hak-hak perempuan dalam politik dan ekspresi diri, namun tetap bangga dengan sistem monarki yang ada. Mereka tidak menuntut adanya pemilihan gubernur secara langsung, melainkan menerima dan mendukung Sultan sebagai pemimpin yang ditunjuk.
Hal ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat Yogyakarta, demokrasi tidak selalu harus diwujudkan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Dalam konteks Yogyakarta, dukungan terhadap monarki dan nilai-nilai liberal dapat berjalan beriringan. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi dapat memiliki berbagai bentuk yang disesuaikan dengan konteks budaya dan sejarah suatu masyarakat.
Meskipun mereka mendukung nilai-nilai liberal seperti hak-hak perempuan dalam politik, mereka tetap bangga dengan sistem monarki yang ada. Sikap ini mencerminkan identitas kolektif dan habituasi terhadap pemerintahan monarki yang telah berlangsung lama.
Argumentasi-argumentasi di atas menunjukkan bahwa dukungan terhadap monarki di Yogyakarta bukanlah tanda ketidakdemokratisan, melainkan bentuk demokrasi itu sendiri yang unik dan khas sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Masyarakat Yogyakarta telah menunjukkan partisipasi politik yang tinggi dalam pemilihan umum lainnya, tetapi tetap memilih untuk mempertahankan monarki untuk posisi gubernur. Ini menunjukkan bahwa mereka melihat monarki sebagai bagian integral dari identitas dan sejarah mereka.
Apa yang menjadi latar belakang dari keistimewaan Yogyakarta perlu dipahami oleh masyarakat luar Yogyakarta, agar dapat melihat bahwa monarki di Yogyakarta adalah hasil dari pilihan demokratis masyarakatnya. Sehingga konflik dan perdebatan yang tidak produktif mengenai sistem pemerintahan DIY ini tidak diperlukan, karena monarki di Yogyakarta adalah cerminan dari kehendak rakyat yang menghargai tradisi dan sejarah mereka.
Yaser Fahrizal Damar Utama,S.I.Kom. Pemerhati Budaya
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.