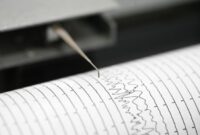Di bawah bayang-bayang kekuasaan Hitler di Reich Ketiga, berbagai percobaan pembunuhan terhadap sang diktator dilakukan—namun semuanya gagal. Upaya paling terkenal untuk menggulingkan rezim nasionalis-sosialis NAZI adalah “Operasi Walkre atau Valkyrie” pada tanggal 20 Juli 1944.
Lebih dari 200 orang terlibat, dipimpin oleh perwira tinggi Angkatan Darat Jerman, Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Tapi bukan hanya Stauffenberg dan para koleganya sesama perwira. Sejumlah perempuan pun ikut ambil bagian. Di antaranya Erika von Tresckow, istri Mayor Henning von Tresckow yang juga terlibat dalam rencana.
Erika menyampaikan pesan-pesan penting untuk mengoordinasikan kelompok perlawanan sipil dan militer, serta mengetik ulang salinan bersih rancangan perintah operasi itu.
Ketika upaya pembunuhan itu gagal, Henning von Tresckow bunuh diri. Erika ditangkap Gestapo, namun berhasil meyakinkan bahwa ia tidak mengetahui rencana tersebut. Ia akhirnya dibebaskan.
Erika von Tresckow adalah satu dari 260 perempuan yang kisahnya ditampilkan dalam pameran khusus “Perempuan dalam Perlawanan terhadap Nasionalisme Sosialis” di Gedenksttte Deutscher Widerstand (Pusat Peringatan Perlawanan), Berlin, tahun 2024.
Pameran ini adalah hasil dari penelitian panjang yang didukung Bundestag Jerman, tentang peran perempuan yang bangkit melawan kekuasaan NAZI di Reich Ketiga.
Menurut Kepala Memorial Johannes Tuchel, kisah-kisah ini menunjukkan berbagai bentuk perlawanan: Dari perempuan yang memilih kehidupan di pengasingan, kaum Kristen, sosial-demokrat, sosialis, hingga anggota Swingjugend—kelompok muda yang mencintai musik swing dan jazz yang dibenci NAZI karena dianggap mewakili budaya Yahudi dan Afrika-Amerika.
Swingjugend berdiri sebagai simbol gaya hidup alternatif. “Dari sanalah, hanya selangkah menuju perilaku dianggap menyimpang—sesuatu yang bertentangan langsung dengan proyek NAZI,” ujar Tuchel.
Ia mengutip musisi jazz Jerman dan penyintas Holocaust, Coco Schumann: “Seseorang yang mendengarkan swing, takkan bisa berbaris dalam irama yang seragam.”
Di antara perempuan yang menolak “berbaris seragam” ini, ada kaum komunis, anarkis, perempuan Yahudi, saksi Yehova, dan lesbian. Mereka semua merasa harus melawan fasisme—karena keberadaan mereka saja sudah menjadi bentuk perlawanan terhadap ideologi NAZI.
Beberapa perempuan yang dihormati dalam pameran itu telah dikenal sebelumnya. “Sebuah pameran tentang perempuan dalam perlawanan takkan lengkap tanpa menyebut Sophie Scholl,” papar Tuchel—anggota satu-satunya yang perempuan dari lingkar dalam kelompok mahasiswa Weie Rose (Mawar Putih). Ia dieksekusi pada usia 21 tahun karena menyebarkan selebaran anti-NAZI.
Kisah Marlene Dietrich, bintang film Jerman, juga ditampilkan. Ia meninggalkan tanah air sebelum NAZI berkuasa dan pindah ke Hollywood. Saat Amerika Serikat ikut berperang, ia tampil menghibur tentara dan tawanan Jerman di Afrika Utara, Italia, Prancis, dan Belgia. Ia juga terlibat dalam propaganda yang bertujuan melemahkan moral warga dan tentara Jerman.
Nama-nama lain mungkin kurang dikenal, tapi kisah mereka telah menginspirasi penulis dan sineas. Erich Maria Remarque, penulis novel antiperang Im Westen nichts Neues (yang dilarang NAZI), mendedikasikan novel Der Funke Leben (1952) untuk adik perempuannya, Elfriede Scholz. Ia dihukum mati karena menyebut “kemenangan akhir” Jerman sebagai propaganda belaka, menyamakan tentara sebagai “ternak sembelihan”, dan berharap Hitler mati.
Elise dan Otto Hampel, suami-istri, menyebarkan hampir 300 kartu pos tulisan tangan berisi pesan anti-NAZI, menyusul kematian adik Elise dalam perang. Mereka meletakkan kartu-kartu itu di kotak pos dan tangga-tangga gedung di Berlin. Pasangan ini juga dieksekusi.
Kisah mereka menjadi dasar novel “Jeder stirbt fr sich allein” (Setiap Orang Mati Sendirian) karya Hans Fallada yang belakangan banyak difilmkan.
Tahun 1943, saat Sophie Scholl, Elfriede Scholz, dan pasangan Hampel dihukum mati, penindasan terhadap perempuan dalam perlawanan semakin keras. “Dulu, pelanggaran seperti itu bisa dihukum penjara enam bulan. Kini, sering kali berujung pada hukuman mati,” jelas Tuchel. Ironisnya, justru saat tekanan itu meningkat, perlawanan perempuan pun makin tumbuh.
“Sebab saat itu, hampir tak ada lagi laki-laki di Jerman,” lanjutnya. Pada 1944, delapan juta laki-laki bertugas di militer. Perempuan mulai mengisi peran yang dulu hanya dipegang laki-laki: Bekerja di pabrik, mengurus keluarga, dan tetap bertahan. “Meski bayang-bayang peran tradisional masih kuat, kesadaran untuk bertanya dan bersikap kritis pun mulai tumbuh.”
Rezim NAZIt akut akan kerusuhan di dalam negeri. Karena itu, ujar Tuchel, pernyataan-pernyataan kritis dari perempuan “tak lagi dianggap lelucon atau keluhan, tapi dari tahun 1943 disebut sebagai ‘Wehrkraftzersetzung’—perusakan kekuatan pertahanan negara—yang bisa dihukum mati.”
Dari keberanian perempuan-perempuan itu, kita bisa menarik pelajaran hingga kini. “Kita bisa melakukan sesuatu untuk melawan kediktatoran,” pungkas Tuchel. “Ya, itu berisiko. Tapi bukan berarti kita harus menyerah pada arus zaman—apa pun bentuk tantangan totalitarian itu. Selalu ada sesuatu yang bisa kita lakukan.”
Artikel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
Editor: Hendra Pasuhuk