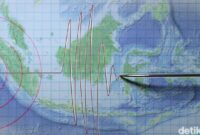Global Report on Food Crises 2025 mengungkapkan lebih dari 295,3 juta orang di 53 negara terancam kelaparan akut. Jumlah ini meningkat 13,7 juta orang dibandingkan tahun 2023. Sementara itu, Global Hunger Index (GHI) 2025 melaporkan Indonesia menduduki peringkat 70 dalam indeks kelaparan global.
Indonesia meraih skor 14,6 atau berada ditingkat kelaparan sedang. Angka ini membuat Indonesia berada pada taraf yang cukup tinggi dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Thailand (9,7), Vietnam (11,1), Filipina (13,4), dan Malaysia (13,6).
Kedua data mengungkap bahwa masalah pangan yang terjadi tak sekadar soal produksi. Sering kali, kelaparan tumbuh dari kegagalan akses atas pangan.
Inilah inti pemikiran Amartya Sen: kelaparan terjadi bukan karena tak ada pangan di dunia, akan tetapi karena rakyat banyak kehilangan hak atas pangan-baik disebabkan kemiskinan, konflik, diskriminasi, atau kebijakan distribusi yang timpang.
Saat ini dunia sedang menghadapi fase “katastrofik” atau bencana besar yang terpusat di beberapa titik konflik seperti Palestina dan Sudan. Selain itu, pemangkasan besar-besaran subsidi, proteksi negara sentra pangan, dan perang dagang memperparah situasi.
Realitas itu menegaskan bahwa krisis pangan sekarang lebih sering merupakan hasil kombinasi politik-konflik dan ekonomi-politik daripada hanya kegagalan produksi global.
Angin segar datang dari negara-negara yang menyadari pangan merupakan hajat hidup orang banyak, seperti Indonesia. Bung Karno berpesan: “Urusan pangan adalah soal hidup mati sebuah bangsa”.
Prabowo Subianto dalam Paradoks Indonesia dan Solusinya juga menekankan: “Kita bisa hidup tanpa gedung-gedung pencakar langit. Kita bisa hidup tanpa mobil-mobil. Namun kita tidak bisa hidup tanpa pangan. Karena pangan adalah strategic commodity. Pangan bukan sekadar economic commodity”.
Swasembada Pangan yang tengah digalakan dan dikerjakan pemerintah bertujuan mulia. Meski sarat implikasi politik dan sosial, Swasembada Pangan harus berjalan secara komprehensif. Perhatian juga mesti ditujukan pada distribusi, daya beli, dan akses sosial-politik. Artinya, solusi teknis saja melalui peningkatkan produksi tidak lah cukup tanpa mekanisme akses yang berkeadilan.
Atas dasar itu, Presiden Prabowo Subianto pada pidato pertama usai pelantikan menyatakan, “Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya”. Pangan memang menjadi konsen Prabowo Subianto sejak awal, jauh sebelum menjadi Presiden RI. Hal ini dibuktikan dengan terdapat 7 (tujuh) kata pangan dalam Manifesto Perjuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Presiden Prabowo Subianto menempatkan Swasembada Pangan dalam 17 pogram prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat Visi Asta Cita. Tujuan ini kemudian tertuang dalam Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
Tepatnya pada prioritas nasional 2 dengan strategi swasembada pangan yang mencakup Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) di lokasi prioritas, pengembangan pangan akuatik (blue food), pangan hewani, pangan lokal, serta pangan nabati.
Indonesia menunjukkan capaian produksi padi yang kuat sepanjang 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi produksi beras nasional pada rentang Januari-Desember 2025 mencapai 34,77 juta ton, atau naik 13,54% dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan ini didukung oleh perluasan luas panen padi menjadi 11,35 juta hektare. Jika mengacu perkiraan Badan Pangan Nasional, konsumsi rata-rata beras nasional sekitar 31 juta ton per tahun, Indonesia bisa dikatakan telah menyandang Swasembada Beras pada 2025.
Tantangan yang dihadapi, produksi beras yang tinggi tidak diikuti stabilisasi pasokan dan harga pangan. Sepanjang tahun 2025, rata-rata harga beras medium ditingkat konsumen melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp. 13.500/kg.
Hal ini terjadi karena Badan Pangan Nasional RI sebagai regulator dan Perum Bulog yang menjadi operator memiliki berbagai keterbatasan. Artinya akses dan keterjangkauan harus menjadi penjamin swasembada pangan yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, untuk mengurai hak atas pangan yang adil dibutuhkan suatu reformulasi regulasi. Komisi IV DPR-RI saat ini sedang menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Sebelumnya kelahiran UU Pangan 18/2012 ditandai sebagai tanggapan terhadap krisis pangan global tahun 2008. Namun setelah lebih dari satu dekade, berbagai persoalan pangan terdahulu masih terjadi dan muncul tantangan baru.
Setidaknya terdapat delapan masalah. Pertama, ketergantungan impor pangan masih tinggi. Terkhusus setelah kehadiran UU Cipta Kerja. Kedua, akses petani terhadap tanah, modal, benih, pupuk, dan pasar belum memadai. Ketiga, negara belum optimal memenuhi kewajiban konstitusional atas pangan bagi rakyat banyak. Keempat, kerawanan pangan dan gizi masih terjadi di banyak daerah.
Kelima, desakan internasional terutama Organsiasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mempengaruhi ruang kebijakan nasional. Keenam, sistem informasi pangan belum terintegrasi dan transisi ke digitalisasi belum optimal. Ketujuh, perubahan iklim yang mengancam produksi pangan. Kemudian kedelapan, kelembagaan pangan yang belum optimal, terutama kendala koordinasi lintas sektor dan paradoks kewenangan yang terjadi.
Semangat tersebut menekankan bahwa perubahan UU Pangan harus meneguhkan pangan sebagai kebijakan strategis. Kita ingin memastikan pangan diproduksi dari dalam negeri, oleh petani kita sendiri.
Karena itu, pembaruan UU Pangan menjadi momentum memperkuat Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan atau yang diterjemahkan sebagai Swasembada Pangan, dan Ketahanan Pangan secara jelas dan terukur.
RUU Pangan tahun 2025 dirancang untuk memperkuat perlindungan hak atas pangan sebagai hak dasar rakyat. Kemudian mempertegas peran negara sebagai penanggung jawab pemenuhan pangan. Juga menguatkan posisi petani, nelayan, peternak, dan produsen pangan skala kecil sebagai subjek utama sistem pangan, untuk mendapatkan aset, akses, dan insentif yang adil.
Hal yang penting terkait penataan kebijakan impor secara selektif dan berbasis kebutuhan nasional. Menjamin kepastian usaha, harga yang layak bagi petani, dan harga terjangkau bagi konsumen. Termasuk penjaminan keamanan, mutu, dan keberlanjutan pangan dengan digitalisasi sistem pangan nasional dari hulu hingga hilir berbasis teknologi & data.
Sistem pangan harus dibangun berlandaskan resiliensi terhadap krisis dan perubahan iklim. Terutama dalam memperkuat cadangan pangan nasional. Lalu penataan ulang kelembagaan pangan nasional untuk mempercepat respons dalam setiap kondisi.
Berdasarkan itu terdapat delapan catatan yang patut menjadi rekomendasi dalam merumuskan perubahan UU Pangan. Pertama, harus memperjelas kerawanan pangan agar tidak normatif.
Mesti terdapat indikator kerawanan, ambang batas, maupun protokol respon cepat. Semisal menggunakan standar IPC/FAO (Integrated Food Security Phase Classification), menetapkan protokol tanggap darurat 24-72 jam, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk daerah.
Kedua, memasukan instrumen penyelamatan pangan baik dari sisi hulu (food loss) atau sisa makanan pada tahap hilir (food waste). Ketentuan harus mengandung target nasional, insentif industri, atau standar pangan redistribusi.
Lalu target nasional untuk pengurangan sisa pangan, memberikan insentif pajak, dan mengatur standar BPOM untuk pangan layak redistribusi. Ketiga, sistem informasi pangan perlu menjamin standarisasi data.
Potensi tumpang tindih data antar Kementerian/Lembaga masih ada. Sebab belum ada aturan interoperabilitas. Karena itu, penerapan single data standard, integrasi antar K/L, serta kewajiban traceability berbasis digital sangat mendesak dalam hal pangan.
Keempat, menimbang penggunaan cadangan pangan masyarakat. Pada satu sisi penggunaan stok pangan masyarakat dapat menurunkan minat swasta menyimpan stok. Namun pada sisi lain angka cadangan pangan nasional menjadi lebih presisi, sehingga membantu keputusan diambil lebih cepat dan tepat.
Kelima, meninjau posisi kelembagaan pangan nasional. Peleburan Badan Pangan Nasional ke BULOG, atau mengembalikan BULOG sebagai badan yang langsung berada di bawah Presiden, harus dilengkapi kajian dampak. Misalnya dampak hilangnya fungsi koordinasi kelembagaan pangan nasional.
Karena itu, patut dilakukan impact assessment dan pertimbangkan akibat memisahkan regulator (Bapenas) dan operator (BULOG). Terlebih saat ini juga ada Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Keenam, penganggaran yang jelas untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Anggaran yang dikelola Kelembagaan Pangan Nasional di masa depan harus dilengkapi mekanisme akuntabilitas yang jelas. Kemudian disertai metode penghitungan untuk meminimalisir risiko moral hazard.
RUU harus mewajibkan audit independen, komite pengawasan, dan justifikasi kebutuhan modal. Selanjutnya yang ketujuh, kewajiban daerah terkait pangan mesti didukung pendanaan dari pusat. Mesti disusun bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Pangan atau skema pendanaan khusus untuk Pemerintah Daerah.
Kedelapan, mengatur peran petani dan produsen pangan lainnya, swasta, dan masyarakat sipil dalam penyelamatan pangan. Penyelamatan pangan modern membutuhkan kanal food bank dan sektor filantropi.
Mesti dipertimbangkan tambahan pasal keterlibatan food bank, masyarakat sipil, dan digital marketplace pangan. Selanjutnya mengenai jaminan mekanisme kewajiban negara untuk membeli hasil panen petani, terutama pangan strategis.
Angga Hermanda. Ketua Bidang Kajian dan Diklat Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Pertanian. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA Faperta Untirta).
Simak juga Video: Menjaga Stabilitas Pangan, Menjawab Tantangan Bangsa